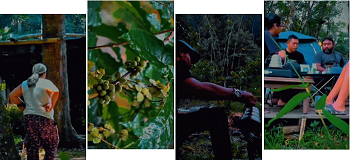Meski Lombok adalah pulau yang relatif kecil, ia punya sejarah kebudayaan sendiri; dan sejarah kebudayaan itu tidak terlepas dari irisan dengan sejarah kebudayaan dari wilayah-wilayah lain. Begitulah, sudah sejak lama manusia dari berbagai wilayah saling bersinggungan; menimbulkan gejala-gejala yang identik dalam perilaku budaya, sehingga sedikit sekali ada perilaku budaya yang sungguh-sungguh berbeda.
Karena menulis teks sastra tidak lain adalah perilaku budaya juga, Lombok pun memiliki sejarah sastranya sendiri.
Dalam perkara (ke)budaya(an) tak dapat dimungkiri bahwa Lombok bersinggungan erat dengan Bali. Di samping posisi geografis yang berdekatan, ada juga faktor politik dan kekuasaan di abad-abad lampau. Wajar jika akar budaya banyak sastrawan dari Lombok tertancap dan berpegangan kuat di Bali. Salah seorang di antaranya adalah Putu Arya Tirtawirya (1940-2009).
Secara pribadi saya mengenal Putu Arya Tirtawirya jauh setelah saya membaca nama dan karya-karyanya di beragam penerbitan. Nama Putu Arya Tirtawirya tercantum, misalnya, dalam buku Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern suntingan Pamusuk Eneste (1982). Beberapa cerpennya juga terpilih dalam kompilasi-kompilasi selektif, seperti Cerita Pendek Indonesia III, suntingan Satyagraha Hoerip (1986); Dua Kelamin Bagi Midin, Cerpen Kompas Pilihan 1970-1980, suntingan Seno Gumira Adjidarma (2003); Menagerie 4, suntingan John H. McGlynn (2000). Beberapa cerpennya juga sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Jerman.
Dalam buku-buku tersebut, Putu Arya Tirtawirya adalah satu-satunya pengarang dari Lombok.
Kecuali itu, tercatat pula karya-karya lepasnya, berupa cerita pendek, puisi, dan beragam esai, yang dirilis koran dan majalah-majalah ternama, juga buku-buku pribadinya yang diterbitkan penerbit-penerbit besar, seperti Balai Pustaka, Pustaka Jaya, atau Nusa Indah.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa Putu Arya Tirtawirya ialah pengarang dari Lombok yang paling dikenal di khazanah sastra Indonesia, terutama pada dekade 60-80-an. Secara khusus tampaknya ia lebih ditandai sebagai penulis cerita pendek, ketimbang penyair atau esais. Oleh sebab itu pembicaraan mengenai cerpen-cerpennya memang tepat apabila dimaksudkan sebagai tribute bagi sosok Putu Arya Tirtawirya dalam konteks sastra Indonesia.
Cerpen-cerpen Putu Arya Tirtawirya, sebagian besar, bertema percintaan dan perkawinan; terutama teantang bagaimana seorang laki-laki mendapatkan jodohnya. Ceritanya datar, lurus-lurus saja, nyaris tanpa kejutan, dan hampir selalu berakhir dengan beresnya persoalan. Karakter-karakternya polos dan tradisional, meski banyak dari karakter-karakter itu adalah seorang pengarang. Hampir semua karakter berasal dari kebudayaan Hindu-Bali, dan persoalan dalam cerita berkisar pada masalah sehari-hari di lingkup keluarga, termasuk soal sistem adat.
Dalam soal sistem adat ini tebersit upaya menyusupkan sikap tentang harga manusia dan nilai kemanusiaan. Cerpen “Jatuhnya Seorang Dewa”, misalnya, berkisah tentang seorang pendeta Brahmana yang dimintakan restu untuk perkawinan beda kasta. Pada mulanya ia menolak memberi restu, tapi setelah si utusan mempelai pergi sembari bersungut-sungut dan menyebut penolakan si pendeta sebagai tindakan diskriminatif, si pendeta, setelah berpikir-pikir, lantas mengubah keputusannya. Begitu juga dalam cerpen “Orang Kaya”; kisah yang berisi percekcokan antara bibi dan keponakan perihal bagaimana suatu lamaran mesti disikapi. Si bibi yang merasa punya banyak jasa karena merawat saudara-saudara si keponakan, termasuk calon mempelai perempuan, merasa bahwa sikap si keponakan terlalu berbelit-belit. Tuduhan si bibi mengandung bias sebab calon mempelai laki-laki tak lain ialah keluarga suaminya. Karena si bibi berpendapat seperti itu, utusan dari pihaknya yang akan mewakili beresnya urusan perkawinan tak kunjung datang, menimbulkan kesan bahwa ibu calon mempelai perempuan telah membuang anaknya. Si keponakan lalu menulis surat kepada calon mempelai laki-laki; suatu surat yang menunjukkan sikap atas harga manusia.
Terus terang kami tidak ingin mengagungkan diri dan tidak pula ingin diinjak-injak. Jalan tengah itulah yang hendak kami jengkau , tapi orang lain menapsirkannya salah. Kami tahu hutang budi harus dibayar dengan budi. Tapi janganlah menuntut yang tidak pada tempatnya. Semiskin-miskin orang, ia tak akan melepaskan mahkota dirinya yang terakhir: harga dirinya sebagai manusia — kehormatan diri dan keluarga. Demikianlah dan kirimlah utusanmu sekali lagi.
(“Jatuhnya Seorang Dewa”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal.19).
Meski tetap berbicara soal perkawinan, kedua cerpen di atas mengandung pandangan tertentu, sehingga peristiwa perkawinan hadir lebih sebagai motif bagi munculnya pandangan tersebut. Hal itu bisa dimungkinkan sebab dalam kedua cerpen di atas, sang mempelai yang menjadi pemicu konflik tidak dihadirkan. Siasat seperti itu tak banyak dipakai oleh Putu Arya Tirtawirya; kebanyakan cerpen-cerpennya menghadirkan para calon mempelai sebagai karakter utama.
Dalam cerpen-cerpen yang menjadikan calon mempelai sebagai karakter utama tampak bahwa apa yang paling penting bagi Putu bukanlah “cerita” melainkan bagaimana cerita itu bergulir. Cerpen-cerpen seperti itu saya sebut “studi adegan”, di mana adegan demi adegan dibangun melalui kecakapan sastra. Untuk menjalankan studi tersebut, Putu agaknya memberi perhatian serius pada detail indrawi. Teks dikelola dan disusun sedemikian rupa dengan tumpu indrawi untuk bisa memunculkan gambaran yang senyata-nyatanya. Penggambaran yang dikerjakan Putu tak bisa dibilang berlarat-larat; pernyataan langsung bersilang selip dengan pernyataan tak langsung melalui kalimat-kalimat yang cenderung ringkas.
Senapan angin milik paman bergayut sebentar pada tali sandangnya, kemudian tergeletak di atas rumput. Dan aku lalu duduk di sampingnya, menjulurkan kaki sambil tangan merogoh saku pantalon hijau tua. Dan sambil menokok-nokokkan sigaret pada lutut, mata kulemparkan ke bawah, ke lembah yang landai.
Atap-atap rumah yang terpencar cukup jauh satu dengan yang lain. Ada yang berwarna merah kehitaman—genteng yang sudah mengalami beberapa musim hujan. Itu rumah paman, kataku dalam hati sewaktu memandang atap genteng yang masih merah kekuningan. Genteng yang baru beberapa bulan menatap langit. Berada di kaki bukit di mana liukan jalan setapak yang kutempuh tadi menghilang. Jalanan yang cuma tampak seperti anak panah yang bengkok tanpa mata, ujungnya seolah tertancap pada rumpun papaina muda yang dipeluk oleh semak-semak perdu.
Rokok kunyalakan. Asapnya kuhembuskan ke arah timur di mana pegunungan yang berbentuk sepatu kuda menghadang, mengepung setengah lingkaran bukit kecil tempatku berada itu. Dan jauh di sebelah barat terbentang dengan tenangnya laut yang biru dan segugus pulau kecil sebagai latar belakang dengan samar-samar.
Itu rumah bocah itu, pikirku —atap rumahnya persis di depanku jauh di bawah, sebelah selatan. Tiga pohon kelapa yang pelepah daunnya saling menimpa sesamanya, tegak di samping rumahnya.
(“Rumah di Kaki Bukit” dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal. 44).
Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana adegan disusun; bergerak dari tindakan karakter, ke apa-apa yang dilihat karakter, menuju persepsi dan motif karakter terhadap apa-apa yang dilihatnya. Struktur tersusun pelan-pelan; lihat, pada kalimat pertama si karakter belum dimunculkan, seakan senapan itu sendiri yang bergayut dan kemudian tergeletak. Ketika karakter mulai muncul, pemandangan meluas hingga melingkupi si karakter.
Apabila contoh di atas menjabarkan pencandraan atas pemandangan yang luas, contoh di bawah ini menampilkan detail:
Dan dia tak dapat menguasai tangannya yang gemetar membuka lipatan kain pembungkus rantang yang berisi cangkir kopi yang panas itu. Cangkir itu diangkatnya dari rantang dan pada bibir rantang, pantat cangkir itu digosok-gosokkannya untuk menepiskan air kopi yang tertumpah dan melelehi cangkir itu. Pada dasar rantang tergenang pula tumpahan air kopi, sedikit merendam pantat cangkir itu selama dalam perjalanan tadi. Cangkir itu lalu ditaruhnya di atas lemari kecil di samping kepala iparnya. Perempuan itu tak memperhatikannya selama itu. Dia sedang mengelus-elus kepala bayinya yang sedang menetek.
(“Hati Seorang Bunda”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal.31).
Melalui sorotan atas cangkir kopi, adegan di atas ternyata bukan sekadar detail gambar, melainkan juga cerminan situasi psikologis karakter. Cerpen “Hati Seorang Bunda” berisi momen-momen di mana seorang laki-laki mesti menyembunyikan kabar kematian saudaranya kepada iparnya, yakni istri saudaranya, persis ketika iparnya itu melahirkan anak. Dari gambaran di atas bisa dilihat betapa perempuan itu tak memperhatikan tangan yang gemetar, dan apalagi seluruh detail adegan cangkir yang proyektif tersebut.
Selain menghidupkan adegan melalui pencandraaan, Putu agaknya juga punya kegemaran menampilkan aspek pendengaran. Hampir di semua cerpennya, citraan auditif atau tindakan mendengarkan yang dilakukan karakter selalu hadir.
Kehitaman malam mulai luntur. Suara kepak sayap dan kruyuk ayam-ayam kampung berantai dari segala penjuru. Bunyi roda pedati yang gemeretak di jalanan. Suara orang menyapu halaman. Batuk-batuk berdahak dan bunyi kerek di sumur samping rumah, semuanya campur aduk menerpa genderang telinga Putu Sasih.
(“Di Kaki Bukit Pangsung”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal. 65).
Oh Dewa Betara…kalimat yang itu-itu juga berulang keluar dari mulut nenek yang mengeluh sepanjang malam sampai akhirnya terdengar suara lumping besi sirihnya jatuh menggelinding di lantai…
(“Nenek”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal. 12-13).
Dalam studi adegan yang dikerjakan Putu, pencandraan dan pendengaran ditempatkan sebagai alat untuk berkelit dari penjabaran langsung; ia tampaknya hendak menerapkan hukum show, don’t tell dengan sungguh-sungguh. Pada kutipan-kutipan di atas bisa dibaca penerapan hukum tersebut, yang juga sangat jelas dalam kutipan lain di bawah ini:
Tenaga gadis itu habis justru di atas titian. Lututnya lemas dan pabila aku tidak dengan cepat menangkap tangannya, bunyi berdebur akan terdengar di bawah titian dari batang kelapa.
(“Malam Pengantin” dalam Malam Pengantin, Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.8)
Dan di bawah sorotan lampu listrik dik Dar menengadahkan wajahnya yang cantik. Ditiupnyalah dengan hati-hati bola mata perempuan muda itu. Apakah tangan dik Dar sengaja atau tidak sengaja bergerak menyentuh handuk, dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia tak banyak berpikir saat itu dan Darmi tidak meronta-ronta.
(“Darmi”, dalam Malam Pengantin, Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.21).
Bahwa sebagian besar cerpen-cerpen Putu Arya Tirtawirya bisa disebut sebagai studi adegan, agaknya diakui sendiri olehnya; setidaknya melalui sang narator dalam cerpen “Di Kaki Bukit Pangsung”. Cerpen itu berkisah tentang tiga pasangan laki-perempuan yang menemukan, di antara mereka sendiri, jodohnya masing-masing. Cerpen ini cukup panjang, terdiri dari 8 bagian, dan sebagaimana banyak cerpen lainnya berjalan dengan cerita yang lurus-lurus saja. Akan tetapi, di awal bagian terakhir, sang narator berujar:
Peristiwa di kaki bukit Pangsung telah beberapa bulan berlalu. Dan anda, tanpa mengalami dada berdebar, pasti dapat menangkap dan meramalkan perkembangan cerita ini yang memang berakhir dengan suatu happy-ending. Tidak ada ketegangan, kata anda. Ya, memang bukan itulah titik berat cerita ini karena dia bukanlah berupa sebuah cerita silat atau pistol-pistolan. Saya telah berusaha mengungkapkan salah satu segi dari puisi kehidupan, yang romantis, yang saya coba menuliskannya lewat kelincahan kamera yang memotret adegan-adegan dari pelbagai sudut.
(“Di Kaki Bukit Pangsung”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal.77).
Pembocoran suara pengarang melalui sang narator itu jadi semacam disclaimer untuk motif studi yang dijalankan. Memang, dalam cerpen “Di Kaki Bukit Pangsung”, sudut pandang berpindah dengan lincah tanpa pemisahan-pemisahan bagian, sesuatu yang biasanya dipakai apabila pengarang hendak memakai banyak sudut pandang. Semua karakter utama, yakni ketiga pasang laki-perempuan itu, mendapat ruang untuk menempatkan sudut pandangnya masing-masing.
Studi adegan dan pembocoran narator untuk disclaimer pengarang agaknya membawa pula pada percobaan meta fiksi. Itu tampak dalam dua cerpen, yakni “Kabut Kintamani” dan “Botol yang Keempat”; keduanya dari kumpulan Saat Kematian Semakin Akrab (Nusa Indah, Ende, Cet.I, 1984).
Cerpen “Kabut Kintamani” berkisah tentang seorang perempuan yang cacat kakinya. Ia gemar membaca dan menulis karangan. Karena cacat di kakinya ia pesimis akan hidup, dan terutama kehidupan cintanya. Ia juga tak bisa melanjutkan sekolah dan mesti pulang ke Bali untuk membantu ibunya berjualan di warung makan. Semasa di Lombok, ia sempat mengenal seorang petugas perpustakaan; seorang duda yang tak lain adalah ayah dari teman sekolahnya. Petugas perpustakaan ini juga adalah seorang pengarang. Ia menulis novel berjudul “Kabut Kintamani” yang oleh anaknya diberikan kepada si perempuan. Isi novel itu, sebagaimana isi cerpen ini, tak lain adalah kehidupan si perempuan dan bagaimana akhirnya ia berjodoh dengan si duda, yang serupa pula dengan peristiwa dalam cerpen ini. Cerpen “Kabut Kintamani” seperti sinopsis untuk novel “Kabut Kintamani”.
Praktik metafiksi yang lebih kuat terbaca dalam cerpen “Botol yang Keempat”. Cerpen ini dibuka dengan adegan laki-laki yang tengah (dan telah) meminum berbotol-botol tuak. Laki-laki itu memaki: “Kurang ajar!”. Sesaat kemudian kita tahu itu adalah bagian awal dari sebuah cerpen yang ditulis oleh seorang pengarang. Ia sedang buntu; bagian cerpen itu macet dan si pengarang meremas-remas dan melempar karangan tersebut. Si pengarang kemudian rehat sebentar, berjalan-jalan keluar mencari rokok.
Lantas kita membaca:
Dan saya mengucapkan terimakasih pada langit terbuka cerah di atas kepala saya yang rupanya telah mendinginkan otak saya sehingga para pembaca akhirnya dapat menikmati cerita “Botol yang Keempat” ini:
Maka dimulailah cerita dalam cerpen itu; cerita tentang seorang laki-laki yang marah lantaran mengira kawannya, yang adalah seorang pengarang, telah sembarangan menuliskan, dan artinya mengumbar, masalah rumah tangganya. Setelah mendapat penjelasan dari si pengarang, laki-laki itu pun paham, dan si pengarang juga paham kenapa laki-laki itu uring-uringan: ia mabuk tuak. Dari strukturnya kita bisa melihat betapa bagian awal cerpen ini, maksud saya cerpen “Botol yang Keempat”, yang merupakan fragmen cerpen yang kemudian diremas-remas dan dilemparkan oleh si pengarang, adalah bagian awal dari cerita dalam cerpen ini, sebelum diputus oleh kebuntuan; dan laki-laki yang berseru “kurang ajar!” itu adalah laki-laki yang mendatangi si pengarang. Di dalam cerita itu sendiri, fragmen tersebut tidak dipakai; ia sudah diremas-remas dan dilemparkan. Akan tetapi, di sisi lain, fragmen cerpen yang diremas-remas dan dilemparkan oleh si pengarang dalam cerita itu adalah bagian integral dari cerpen “Botol yang Keempat”. Kalimat lain untuk situasi ini: bagian cerpen yang tidak dipakai oleh si pengarang dalam cerita, dipakai oleh pengarang cerpen “Botol yang Keempat’, yang tokoh utamanya adalah pengarang cerita itu.
Satu percobaan lain diamalkan Putu Arya Tirtawirya lewat salah satu cerpen terbaiknya; “Menghadap Sang Hakim”. Cerpen ini mengangkat konflik tanah; satu dari sedikit cerpennya yang tak menyoal percintaan dan perkawinan. Apa yang menarik dari cerpen ini adalah bagaimana narasi dan kalimat langsung tak diberi tanda pembeda; sampai menjelang akhir cerpen, tak ada tanda kutip yang dipergunakan. Pikiran narator dan karakter cerita selip-menyelip.
Kalau mau menang Pan Kelodan mesti pergi ke rumah pak hakim. Jaman sekarang. Kalau tidak, jangan harap Pan Kelodan bisa menang dalam perkara ini. Pan Kanginan orang pintar, tapi kantongnya kosong. Dasar penjudi — masa , sampai hati menggugat tanah sejengkal.
….
Dalam hal ini Pan Kelodan mesti berani korban. Kerbau Pan Kelodan kan dua. Juallah satu ekor. Apalah arti kerbau, kalau sawah tidak ada lagi? Terlalu Pan Kanginan itu! Belum sempat ganti pipil, tanah sudah dijual dikatakan gadai. Dengan famili sendiri kok sampai hati curang begitu. Tempo hari kenapa Pan Kelodan tidak cepat-cepat ganti nama pipil tanah itu? Saya pikir dengan famili bisa diselesaikan, kapan-kapan.
(“Menghadap Sang Hakim”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.53).
Dari kutipan di atas bisa dibaca bercampurnya suara narator dan suara karakter cerita. Tampaknya sulit diterima bila dikatakan bahwa narasi-narasi di atas adalah suara satu orang saja. Namun, di mana batas-batasnya? Kita melihat sang narator yang memiliki gejala impersonal, bisa jadi sesungguhnya adalah narator personal. Sangat mungkin narasi-narasi di atas, terutama yang kedua, sebetulnya adalah percakapan yang strukturnya disusun seperti narasi. Dua kalimat terakhir dari kutipan di atas, misalnya, apabila disusun (atau dikembalikan) dengan struktur percakapan akan jadi begini:
“Tempo hari kenapa Pan Kelodan tidak cepat-cepat ganti nama pipil tanah itu?”
“Saya pikir dengan famili bisa diselesaikan, kapan-kapan.”
Max Arifin, yang menulis ulasan atas cerpen ini, menyebut bahwa Putu Arya Tirtawirya menerapkan sistem yang dikembangkan oleh James Joyce, yakni stream of consciousness (arus kesadaran). Saya pikir pendapat Max Arifin itu ada benarnya, sebab bila menilik plot cerita, yakni momen Pan Kelodan dalam perjalanan menuju rumah sang hakim, bisa jadi narator cerita ini adalah Pan Kelodan sendiri, setidaknya sampai menjelang akhir cerpen, dan seluruh narasi itu adalah arus pikirannya; arus kesadarannya dalam merespons ingatan dan keadaan.
Percobaan metafiksi dan arus kesadaran dalam cerpen-cerpen Putu Arya Tirtawirya, bisa dimungkinkan tak lain karena praktik studi adegan (dalam kalimat sang narator cerpen “Di Kaki Bukit Pangsung”: saya coba menuliskannya lewat kelincahan kamera yang memotret adegan-adegan dari pelbagai sudut.) adalah basis penciptaan cerpen-cerpennya.
Apabila kita bergerak sirkular ke narasi awal tulisan ini, saya tertarik pada betapa seringnya tokoh-tokoh dalam cerpen Putu Arya Tirtawirya berurusan atau beradegan di depan pintu.
Pintu kamar berdaun dua di mukaku. Tombolnya putar ke kanan dan dorong habis perkara.
(“Malam Pengantin”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.7).
Putu Oka tertegun di ambang pintu gerbang halaman.
(“Darmi”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.22 ).
Bunyi kunci beradu dengan gembok, menyebabkan Wayan Muna mengangkat wajahnya. Seorang polisi tampak setengah badan di balik jalinan kawat pintu.
(“Jin”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.39).
Malam itu di pintu gerbang pekarangan saya menerima tamu.
(“Orang Kaya”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.40).
Pan Kanginan dilihatnya tengah duduk di korsi sambil menoleh ke arah pintu.
(“Menghadap Sang Hakim”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.57).
…dan saya sebagai seorang Brahmana …anaknda pasti dapat mengerti mengapa saya menolak pintu anaknda itu.”
(“Jatuhnya Seorang Dewa”, dalam Pasir Putih Pasir Laut, Balai Pustaka, Cet.II, 1987, hal.18).
Pintu adalah batas yang bisa membuka atau menutup pergerakan orang untuk ke luar atau ke dalam. Dalam urusannya dengan cerpen-cerpen Putu Arya Tirtawirya, pengertian itu diungkapkan karakter utama dalam cerpen “Malam Pengantin”, ketika berhadapan dengan pintu kamar pengantinnya, dengan mengutip definisi penyair menurut Carl Sandburg;
“Penyair adalah pembuka dan penutup pintu sebuah kamar penuh rahasia, di mana pembaca mencoba menjenguk ke dalam…”
(“Malam Pengantin”, dalam Malam Pengantin; Yayasan Dewi Saraswati, Cet.II, 2000, hal.10).
Namun, pintu dalam cerpen-cerpen Putu Arya Tirtawirya bisa jadi juga adalah kode politis yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan di Lombok, yang bersinggungan erat dengan kebudayaan di Bali. Suatu ketika, Putu Arya Tirtawirya pernah menyampaikan pernyataan bahwa dirinya adalah “sastrawan Selat Lombok”; sastrawan antara Bali dan Lombok. Ketika persinggungan kebudayaan pada suatu titik mengerucut pada identitas kebudayaan, perkara mulai muncul. Putu merespons perkara itu dengan menjadikan Selat Lombok sebagai pintu, dari mana ia bisa bergerak ulang-alik, dari atau ke Lombok dan Bali, tanpa perlu menunggalkan identitasnya.*
*Tulisan ini pernah disampaikan dalam acara Microfest:Hereditas, 21 November 2023, di House of Kojo, Mataram.
Kiki Sulistyo, penyair dan pengarang. Ia meraih Penghargaan Sastra Kemendikbudristek (2023), Buku Puisi Terbaik TEMPO (2018 & 2021), serta Kusala Sastra Khatulistiwa (2017). Sejak 2009 ia mengurus Komunitas Akarpohon, Mataram, Nusa Tenggara Barat.